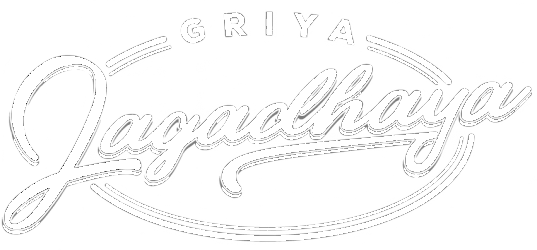Best FM adalah radio komunitas yang berdiri di tengah komunitas santri, tepatnya di Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon. Rakom ini diinisiasi pada tahun 2008 oleh para santri setempat. Meski dari dan oleh santri, rakom ini tidak eksklusif, sebab warga sekitar yang tinggal bedampingan dan menyatu dengan pesantren juga turut menerima manfaatnya. Salah satu yang menarik adalah tidak sekadar menjadi media hiburan dan pendidikan bagi santri dan warga, Best FM juga mengampanyekan nilai-nilai Islam yang moderat dan dengan cara itu mereka menangkal paham-paham ekstrim.
“Sesuai dengan semangat awal berdirinya, Best FM merupakan radio benteng bagi masyarakat pendengar agar terhindar dari radio yang cenderung menyiarkan konten provokatif namun mengatasnamakan radio dakwah,” ujar Ahmad Rofahan, salah seorang pegiat Best FM.
Kalimat pembuka tulisan ini adalah seruan kyai di Buntet Pesantren Cirebon tatkala menanggapi keberadaan radio yang mengampanyekan paham Islam ekstrim dan intoleran. Meski cuma satu, keberadaan radio macam itu nyatanya cukup meresahkan. Saat Best FM tidak mengudara, santri dan warga rentan terpapar paham intoleran berbalut dakwah. Di tengah keterbatasan sumber daya dan adanya ancaman intoleransi cukup masif lewat radio, salah satu kyai di Buntet menyarankan agar radio harus terus hidup, ada atau tidak ada penyiar. Karena hanya dengan cara itulah, penyebaran paham-paham ekstrim bisa ditangkal.
“Beberapa kali secara rutin kami menggelar talkshow dan dialog bersama kyai muda, temanya umum dan bermuatan wacana sosial,” kata Rofahan, seperti dikutip NU Online. Selain melalui radio, para pegiat Best FM juga memanfaatkan internet—situs web dan media sosial—untuk menyiarkan ajaran Islam damai.
Di belahan dunia lain, pada 2016, di Peterborough, Inggris, sebuah komunitas muslim mendirikan radio komunitas bernama Radio Salaam. Radio ini didirikan untuk menangkal stereotip negatif terhadap Islam pascamerebaknya kasus terorisme. Mereka menyiarkan ajaran Islam yang cinta damai untuk mengubah persepsi publik terhadap Islam. Mereka bahkan menggelar pertemuan dengan mengundang pimpinan English Defence League—organisasi sayap kanan anti-Islam,yang notabene ‘musuh’ mereka—untuk berdialog.
“Kami rasa penting untuk mengoreksi banyak ketidakakuratan[argumen] mereka.Kami anti-ekstrimisme, entah itu kelompok kanan jauh (far-right) atau relijius,” kata Amir Sulaeman, salah satu relawan Radio Komunitas Salaam.
“Tidak mudah melakukan ini, sama sekali tidak mudah. Tapi ini adalah hal yang dapat kami lakukan: ada alasan kenapa kami memilih media komunitas—menggunakannya sebagai alat untuk meruntuhkan sekat antarkelompok dengan berbagai latar belakang, baiki tu keyakinan, gender, maupun seksualitas. Radio Salaam, sejak awal, konsisten melaporkan berbagai peristiwa dan menolak ujaran kebencian,” ujarnya.
Kepada The Guardian, Amir mengaku dalam waktu cukup singkat geraknya bersama Radio Salaam membuahkan hasil. “Radio Salaam, dalam kurang dari dua tahun, telah menjadi suara komunitas yang diakui. Tanpa ini, […] kami akan sulit mengatasi isu yang sebetulnya berdampak besar terhadap komunitas. Dengan platform yang netral, kami dapat menyebarkan ajaran Islam sesungguhnya yang cinta damai. Kami melayani komunitas sebagaimana radio komunitas seharusnya,” papar Amir.
Dua kisah di atas adalah segelintir dari sekian banyak pengalaman warga dengan medianya yang berusaha meruntuhkan stereotip maupun menangkal ancaman diskriminasi. Tidak cuma persepsi publik, media komunitas juga menjadi saluran warga minoritas/terdiskriminasi untuk membantah stereotip-stereotip yang dijajakan oleh media arus utama. Pengalaman macam ini tentu tidak hanya menimpa kalangan Muslim saja, ada banyak komunitas marjinal yang memilih melawan dengan membuat media dan memproduksi informasinya sendiri.
Dalam kasus Best FM dan Salaam, media komunitas tidak hanya meresonansi wacana tandingan terhadap ekstrimisme dan terorisme, melainkan juga menjadi penangkal di garda terdepan. Boleh dibilang, ini merupakan wujud ‘aksi langsung’ warga untuk melawan arus ekstrimisme.
Dalam Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution (2017), Ross Tapsell berpendapat bahwa teknologi digital membawa Indonesia ke dua kutub yang berlawanan. Pertama, digitalisasi memungkinkan para oligark untuk menguasai media arus utama dan mendorong sentralisasi struktur kekuasaan di ranah politik dan media. Kedua, munculnya gerakan warga yang memanfaatkan platform media digital untuk tujuan aktivisme dan pembebasan, serta membuka peluang warga untuk menantang dominasi kekuasaan elite melalui pemanfaatan media digital yang efektif.
Pada tahun 2002 ketika UU Penyiaran disahkan—namun teknologi digital belum semasif saat ini—industri media mulai bertransformasi dari yang sangat tertutup di era Orde Baru, menjadi sangat terbuka.Informasi tidak lagi dikuasai dan diawasi oleh negara, namun juga oleh swasta dan warga biasa. Akan tetapi seiring waktu,alih-alih menjadi representasi suara publik,media malah dimonopoli oleh para pemilik modal. Penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (2012) mengungkaphanya 12 grup media yang menguasai hampir seluruh jaringan media di Indonesia. Beberapa di antaranya berafiliasi dengan kelompok politik tertentu dan menjadi corong kepentingan politik pemiliknya. Bahkan kini, di tengah proses revisi UU Penyiaran, perusahaan media masih ngotot mengajukan model penyiaran multi mux agar dapat menguasaipengelolaan kanal siar.
Bagaimana dengan nasib warga? Dalam UU Penyiaran warga memang mendapat ruangnya, meski sangat sempit. Entitas warga yang dalam regulasi diwakili oleh istilah ‘komunitas’ (lembaga penyiaran komunitas; Pasal 21 UU Penyiaran), tidak dapat berbuat banyak. Radio komunitas—dan sedikit televisi komunitas—yang dikelola warga memang tumbuh bak jamur di musim hujan, tapi sebagian besar terhambat karena kesulitan memenuhi prasyarat, terutama soal pembiayaan.
Sekira satu dekade kemudian, gegar internet terjadi—internet sudah muncul sejak akhir ‘90an di Indonesia, namun baru dapat diakses hampir seluruh warga, didesa maupun dikota, pada tahun-tahun setelah 2010. Teknologi digital, seperti kata Tapsell, semakin membuka peluang warga untuk terlibat dalam dinamika arus informasi, termasuk menjadi produsen informasi yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan media. Keterbukaan akses terhadap tekonologi informasi memungkinkan setiap individu atau kelompok warga membangun medianya sendiri. Salah satu tujuan utamanya tidak lain adalah untuk menampung suara-suara marjinal yang selama ini jarang/tidak pernah diakomodasi oleh media arus utama. Dengan cara inilah warga, dalam bahasa Tapsell, “menantang dominasi kekuasaan elite”.
Meski inisiatif media komunitas atau media warga tumbuh subur, dukungan akan eksistensi mereka tidak serta merta datang, terutama dari pemerintah dan publik yang belum memahami perbedaan antara mediayang dipahami umum (arus utama) dengan media komunitas.
Dalam fenomena hoaks dan terorisme, misalnya, media komunitas tidak jarang kena getahnya. Statusnya sebagai media “tidak resmi”, membuatmedia komunitas kerapdisejajarkan dengan media abal-abal yang memuat hasutan dan ujaran kebencian. Kehadiran media abal-abal memang tak bisa dielakkan. Sejumlah kelompok yang mendaku mewakili ‘komunitas muslim’ pun membuat media dengan muatan-muatan hasutan dan kebencian. Rofahan, santri yang juga pegiat media komunitas, menyaksikan sendiri bagaimana di daerahnya, radio dakwah intoleran melabeli dirinya sebagai media komunitas. “Yang sangat disayangkan, radio dakwah yang provokatif itu berlindung dengan mengatasnamakan sebagai radio komunitas,” katanya.
Di zaman ketika setiap orang bisa membuat situs web sendiri, pendikotomian seperti yang diutarakan Tapsell—media korporasi dan media warga—ternyata tidak cukup. Media bisa digunakan oleh kelompok kepentingan yang mengatasnamakan warga demi mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik.
Dalam situasi ini, media komunitas menjadi anomali. Media komunitas tidak bisa ditempatkan dalam kerangka pikir industri media, yang segala infrastruktur legal formalnya diatur dalam kerangka hukum yang ketat. Media komunitas memiliki ciri yang membuat mereka berbeda dari media arus utama, yang merentang dari soal keanggotaan yang inklusif hingga jadwal operasional yang cair. Di sisi lain, media komunitas juga bukan media abal-abal yang dibentuk untuk kepentingan kelompok politik tertentu (tapi bukan berarti media komunitas tidak punya kepentingan politik. Politik media komunitas adalah politik warga). Media komunitas adalah anak kandung kebebasan berekspresi. Ia merupakan manifestasi upaya warga untuk mengintervensi kultur media dominan dengan komitmen mendorong demokratisiasi struktur, bentuk, dan praktik bermedia (Howley, 2005) dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan. Inilah yang membedakan media komunitas dengan media abal-abal.
Kebijakan sertifikasi media oleh Dewan Pers belakangan, misalnya, cenderung mengerdilkan media komunitas. Anggota Dewan Pers yang juga Ketua Harian Serikat Perusahaan Media (SPS), Ahmad Djauhar, pernah mengatakan bahwa, adalah langkah tepat menyaring perusahaan media di tengah maraknya peredaran berita hoaks oleh media abal-abal. Meski tidak ditujukan kepada media komunitas, label ‘perusahaan media’ membuat media komunitas dengan sendirinya tersingkir dari klasifikasi media yang layak simak. Padahal, media komunitas tidak masuk dalam spektrum yang terlaludisimplifikasi dalam kebijakan tersebut; media komunitas bukan perusahaan, dan media komunitas bukan media abal-abal karena memiliki cita-cita menciptakan kultur media—serta merta tatanan masyarakat—yang lebih baik.
Pada akhirnya, seruan untuk memerangi hoaks dan ujaran kebencian ditumpukan kembali kepada media arus utama. Padahal dalam konteks ini, media arus utama juga bukan tanpa kritik. Selain kerap bias dalam memberitakan kelompok minoritas—baca misal, bagaimana media membingkai keluarga kulit hitam Amerika secara rasis—media arus utama juga terkadang, sadar atau tidak, melanggengkan terorisme. Sementara itu, media komunitas dengan keterbatasan dan beban stigma, melakukan aksi langsung menangkal terorisme dengan caranya sendiri.[]
Bahan bacaan
Birowo, Mario Antonius. Saraswati, Idha. Nuswantoro, Ranggabumi. Putra, Ferdhi Fachrudin. 2016. Pergulatan Media Komunitas di Tengah Arus Media Baru: Studi Kasus Lima Media Komunitas di Indonesia. Yogyakarta: Combine Resource Institution
Howley, Kevin. 2005. Community Media: People, Places, and Communication Technology. Cambridge: Cambridge University Press.
Tapsell, Ross. 2017. Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. London: Rowman & Littlefield International Ltd.