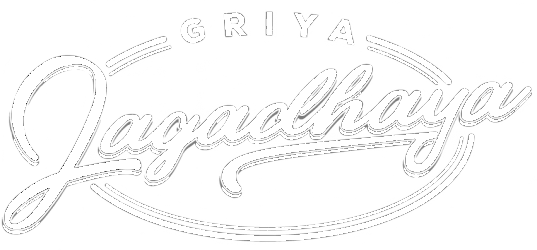(Si)apa yang menjadi korban ketika warga akademi melaporkan sebuah kerja intelektual ke polisi? Korban pertama tentu si terlapor. Tapi korban yang utama adalah hal yang justru paling diusahakan dalam dunia akademik: kebenaran. Sebab, untuk mengusahakan kebenaran, bebas dari rasa takut adalah prasyarat.
Kebenaran adalah korban utama dari langkah Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mempolisikan Zakki Amali, seorang wartawan media alternatif Serat.id. Zakki dilaporkan ke polisi karena pemberitaannya atas dugaan plagiasi Rektor Unnes Fathur Rokhman.
Sebenarnya bukan Serat.id saja yang menurunkan laporan tersebut. Tirto.id, misalnya, juga memberitakan hal yang serupa. Anehnya, tidak seperti yang dialami Serat.id, laporan Tirto.id bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hak jawab, seperti sebagaimana seharusnya keberatan atas pemberitaan ditempuh. Lantas mengapa ada perbedaan perlakuan?
Pihak Unnes berargumen bahwa Serat.id belum berbadan hukum dan belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Zakki sendiri, sang wartawan Serat.id, belum terakreditasi melalui uji kompetensi wartawan.
Apa yang bisa disimpulkan dari perlakuan diskriminatif tersebut adalah pemahaman yang menempatkan “jurnalisme sebagai privilese”. Kerja jurnalistik dianggap hanya boleh dilakukan oleh individu dan lembaga tertentu. Kalau menjadi sebuah privilese, jurnalisme telah gagal menjadi jalan emansipatoris, karena ia menjadi wilayah yang tertutup dan dimonopoli oleh lingkar sosial tertentu. Jurnalisme dalam pandangan ini, bukanlah alat pembebasan, melainkan properti kekuasaan.
Jurnalisme dalam pengertian tersebut tentu mengkhawatirkan. Jurnalisme elitis macam itu tak pelak berpotensi memangsa korban-korban berikutnya. Jurnalisme warga adalah salah satunya.
Jurnalisme warga adalah kegiatan pencarian dan penyebaran informasi menggunakan metode jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa. Para pegiat jurnalisme warga biasanya menulis untuk media komunitas yang sifatnya nonprofit. Mereka memproduksi berita untuk kebutuhan mereka sendiri karena seringkali media korporasi tidak mengakomodasi aspirasi mereka. Sebab itu, jurnalisme warga bukan saja tengah menciptakan ruang publik yang lebih majemuk, tapi ia bisa dilihat sebagai proyek “pendidikan mandiri warga” (Rodriguez dalam Atton, 2009: 266). Lebih jauh, jurnalisme warga juga harus dilihat sebagai bagian dari sistem keseimbangan dalam demokrasi.
Namun, barangkali karena sifatnya yang informal dan khusus itulah, kebanyakan jurnalis warga dan media komunitas tak memusingkan perihal akreditasi dan formalisasi hukum. Sialnya, pandangan “jurnalisme sebagai privilese” akan mengancam kegiatan jurnalistik “non-profesional” yang dilakukan dalam jurnalisme warga, sebagaimana ia telah meneror Zakki Amali dan Serat.id. Sebab itulah, tulisan ini menawarkan pandangan baru dalam mendefinisikan jurnalisme.
Redefinisi Jurnalisme: Dari “For Citizenship” ke “As Citizenship”
Praktik jurnalisme warga sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Pada awalnya, kegiatan jurnalistik adalah kegiatan warga biasa. Lewat catatan sejarah (misalnya Adam, 1995) kita bisa katakan bahwa pers Indonesia di masa pra-kemerdekaan dikerjakan bukan hanya oleh wartawan “profesional”, melainkan juga dikerjakan oleh awam yang merangkap dengan pekerjaan utama lain, seperti pemilik toko kelontong, pedagang kain, guru, atau dokter. Jurnalisme, dalam praktik macam demikian, adalah sebentuk aktivisme untuk melawan penindasan kolonial.
Kalau pada awalnya jurnalisme dimulai sebagai aktivitas warga biasa, lalu apa yang mengubah jurnalisme sebagai pekerjaan “profesional” dan menjadi sebuah privilese? Saya menduga, industrialisasilah yang ikut berperan mengubah praktik dan pemaknaan atas jurnalisme yang kita kenal hari ini. Industrialisasi pers pada awalnya, seperti ditulis Daniel Dhakidae (1991), menggeser orientasi pers yang semulanya partisan dan mengabdi pada ideologi politik, menjadi pers yang berorientasi kepada pasar dan akumulasi kapital. Selain industrialisasi, periode depolitisasi yang dijalankan Orde Baru telah mendorong pers untuk cenderung memilih jalan kapital ketimbang mengejar cita-cita politik atau bersikap antagonistik terhadap kekuasaan.
Orientasi baru pers tersebut kemudian bertumbuh di dalam diskursus utama—yang secara dominan diimpor dari praktik jurnalisme di Eropa dan Amerika Utara—yang memposisikan jurnalisme sebagai upaya untuk menopang partisipasi warga negara di dalam demokrasi. Di sini, jurnalisme dilihat sebagai sumber atau modal bagi praktik kewargaan. Kerja jurnalisme diharapkan untuk bisa menaikkan literasi politik warga dalam kehidupan demokrasi. Dalam pandangan ini, warga yang berdaya adalah warga yang mendapatkan cukup informasi. Untuk membuat warga melek informasi, jurnalisme lah yang diberikan peran untuk menunaikannya. Semakin melek politik warga suatu negara, maka semakin bermutulah praktik demokrasi di sana. Pendeknya, jurnalisme adalah sarana pendidikan bagi voters. Inilah pandangan yang melihat “jurnalisme untuk kewargaan” (journalism for citizenship).
Konsekuensi dari pandangan “jurnalisme untuk kewargaan” adalah pemosisian jurnalisme yang dilihat sebagai tanggung jawab sekelompok profesional untuk membantu warga. Di sini, warga diposisikan sebagai konsumen informasi. Hak seorang konsumen tentu adalah mengonsumsi, dan tanggung jawab seorang konsumen adalah menggunakan ketersediaan informasi yang ada untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Konsumen tidak punya hak dan tanggung jawab memproduksi informasi. Hanya individu atau lembaga tertentu yang dianggap kredibel dan mendapatkan otoritas untuk memproduksi informasi lewat praktik jurnalistik. Akibatnya, jurnalisme dilihat sebagai privilese.
Sayangnya, seperti yang sudah kita saksikan lewat kasus Serat.id, “jurnalisme untuk kewargaan” gagal menempatkan jurnalisme warga dengan lebih adil, yang menyebabkan timbulnya ancaman dari kekuasaan karena tiadanya perlindungan hukum. Karena itu saya ingin mengajukan pandangan untuk melihat “jurnalisme sebagai praktik kewargaan” (journalism as citizenship).
Dalam pandangan ini, jurnalisme dimaknai bukan saja semata sebagai sumber daya bagi praktik kewargaan, melainkan ia merupakan bentuk dari praktik kewargaan itu sendiri (Campbell, 2014).
Artinya, melalui jurnalisme seseorang bisa menyalurkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kerja jurnalistik, dalam pandangan ini, dijalankan oleh seseorang yang mendahulukan kesadaran identitasnya sebagai seorang warga negara ketimbang sebagai seorang wartawan.
Pengertian aspek kewargaan di sini tentu harus melampaui kategori yuridis yang hanya menempatkan seorang warga sebagai subjek hukum secara administratif—yang ditandai dengan tumpukan dokumen yang hanya punya harga ketika berurusan dengan birokrasi. Kewargaan di sini harus dilihat sebagai “bentuk keberanggotaan dalam suatu komunitas yang eksklusif dengan basis ikatan sosial yang khas” (Cohen dalam Robert dan Tobi, 2014: 4). Kewargaan di sini dipahami sebagai peran agensi individu dalam komitmennya berpartisipasi dalam kehidupan publik.
Dalam pengertian tersebut, jurnalisme adalah modus kewargaan dalam sektor informasi. Ia adalah manifestasi dari inisiatif individu untuk terlibat dalam urusan bersama. Pandangan “journalism as citizenship” kemudian akan memberikan landasan moral bagi praktik jurnalisme warga untuk lebih mendapatkan posisi sosial dan perlindungan hukum. Sebab, sebagai wujud dari tugas seorang warga negara, jurnalisme bukan lagi privilese, tapi hak, dan bahkan tanggung jawab. Kalau tawaran pandangan baru tentang jurnalisme ini mapan sebagai sebuah diskursus, seorang akademisi atau pejabat fasis tentu akan berpikir jutaan kali untuk mempidanakan individu yang sedang melaksanakan hak dan menunaikan tanggung jawab publiknya, bukan?
Selain itu, diskursus tersebut punya potensi yang lain: merevitalisasi konsep dan praktik jurnalisme warga, jurnalisme, dan kewargaan secara sekaligus. Begini persisnya.
Pertama, “journalism as citizenship” membangun sebuah definisi yang lebih ketat dan motivasi yang lebih luhur bagi jurnalisme warga: menyeleksi apa-apa yang bukan jurnalisme warga kalau bertentangan dengan gagasan dan nilai kewargaan (civic value). Diobralnya istilah jurnalisme warga dalam dua dekade terakhir dikarenakan kita sibuk membahas “jurnalisme”-nya tapi abai membahas pengertian “warga”-nya. Akibatnya, terjadi pembajakan istilah jurnalisme warga untuk menamai praktik pencarian dan produksi informasi apapun yang dilakukan oleh non-profesional. Selain oleh ormas rasis atau media abal-abal, jurnalisme warga juga telah dibajak untuk menamai praktik kontribusi penonton atau pembaca yang mengirimkan materinya ke media korporasi. Dengan fungsi dan prosedur yang sangat berbeda dengan praktik jurnalisme warga di media komunitas, sangat sulit untuk menganggap produk jurnalistik dengan logika industri, seperti “Wide Shot” (Metro TV) atau “Net Citizen Journalist” (Net TV), sebagai act of citizenship.
Kedua, di tengah ekosistem bisnis media hari ini yang membuat jurnalisme semakin kehilangan relevansi dan tanggung jawab sosialnya, “journalism as citizenship” menyediakan sebuah definisi dan ukuran dengan kualitas politis bagi jurnalisme “profesional”. Pandangan ini merevitalisasi identitas warga negara pada wartawan; bahwa pekerjaan jurnalistik adalah tanggung jawab dan manifestasi politik seorang warga negara. Yang akan terbangun di sini adalah sebuah demarkasi yang jelas dan tegas: antara publik dengan privat; antara kepentingan warga dengan perusahaan media.
Ketiga, “journalism as citizenship” mempromosikan sebuah wilayah lain yang bisa ditempuh untuk bisa berpartisipasi dan berdaya sebagai warga: jurnalisme. Ketika konsep kewargaan ala negara menawarkan makna menjadi warga negara yang tak lebih dari sekadar kepemilikan paspor, ketika diskursus dominan tentang kewargaan tidak menyediakan cara untuk menjadi warga negara yang baik selain bungkam terhadap pembantaian di Papua atas nama nasionalisme, maka mempraktikkan sikap kewargaan lewat jurnalisme bukan saja progresif, tapi juga produktif.
Daftar Pustaka
Adam, Ahmat. 1995. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913. Hasta Mitra: Jakarta.
Atton, Chris. 2009. “Alternative and citizen journalism.”The handbook of journalism studies: 265-278.
Campbell, Vincent. 2014. “Theorizing Citizenship in Citizen Journalism”, Digital Journalism, DOI: 10.1080/21670811.2014.937150
Dhakidae. Daniel. 1991. The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industri.
Robert, Robertus dan Tobi, Hendrik Boli (2014). Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben. Marjin Kiri: Tangerang.
Roy Thaniago adalah Direktur Remotivi dan Dosen di Universitas Multimedia Nusantara.